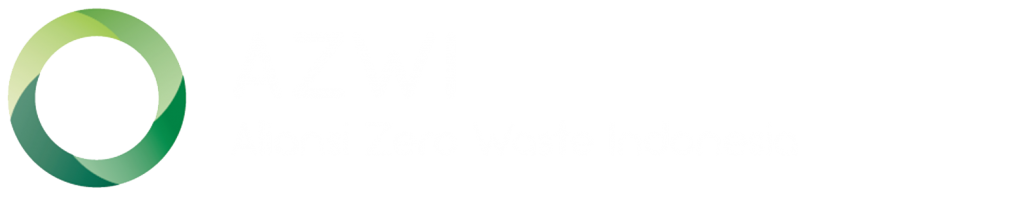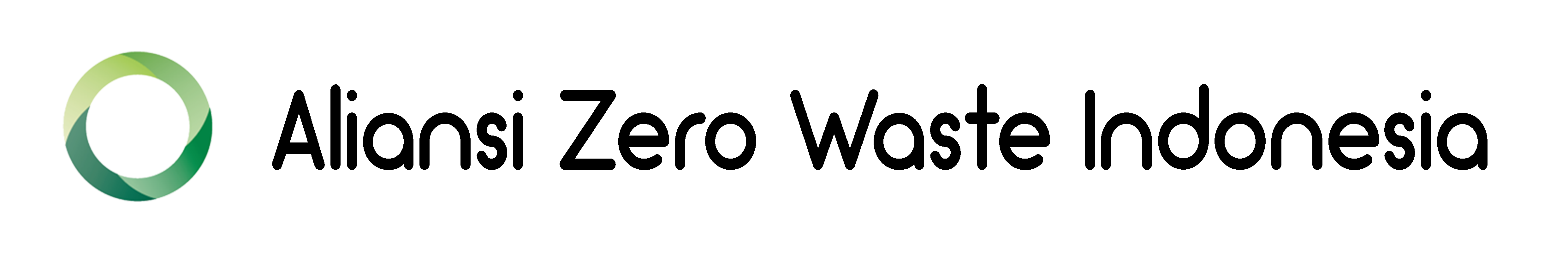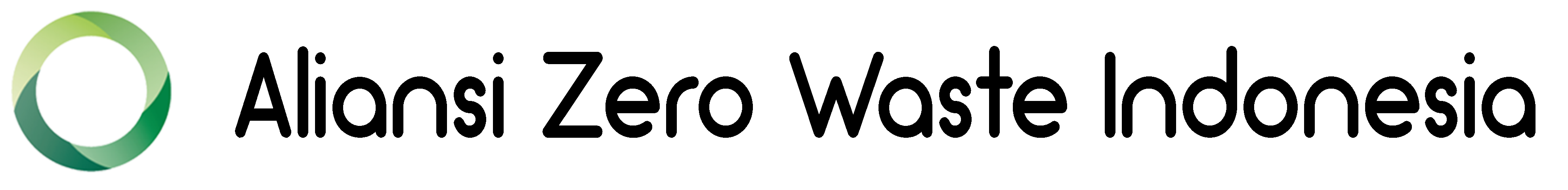Indonesia sering dipuji sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Namun, ironisnya, penerimaan negara dari sektor ini justru kecil: hanya sekitar 7% dari total pendapatan negara menurut BPS. Sebaliknya, 82% pendapatan negara datang dari pajak umum. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi sektor sumber daya alam adalah kebijakan tax holiday, pembebasan pajak yang diberikan pada industri besar, termasuk sektor petrokimia dan plastik. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan negara, atau justru merugikan publik?
Tax holiday sejatinya dirancang sebagai insentif fiskal untuk menarik investasi besar. Pemerintah beralasan kebijakan ini penting agar industri strategis bisa tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi di balik niat baik tersebut, ada konsekuensi besar. Pajak yang hilang jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun, sementara industri yang menerima fasilitas ini adalah salah satu penyumbang kerusakan lingkungan terbesar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2023, total insentif tax holiday yang digelontorkan ke berbagai industri mencapai sekitar Rp 5,18 triliun. Jika jumlah sebesar ini juga mencakup sektor petrokimia, maka terlihat jelas betapa besarnya potensi dana yang hilang bagi negara. Sebagai perbandingan, satu proyek rehabilitasi tambang atau kawasan industri bisa menelan biaya hingga Rp 500 miliar. Artinya, dana Rp 5,18 triliun yang hilang karena tax holiday setara dengan pembiayaan sekitar 10 proyek reklamasi berskala besar. Proyek ini seharusnya mampu memulihkan kerusakan lingkungan dan meringankan beban yang selama ini justru ditanggung masyarakat.
Proses produksi di dalam industri petrokimia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi, ditambah ketergantungan mereka pada energi dari PLTU batu bara yang juga berpolusi. Selain itu, limbah cair dari pabrik kimia kerap bermuara ke sungai, mengancam kualitas air masyarakat sekitar. Penelitian International Pollutants Elimination Network (IPEN) menyoroti bahwa industri berbasis petrokimia juga berkontribusi pada pelepasan mikroplastik dan bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah, air, dan udara. Dampak ini bukan sekadar angka statistik, melainkan nyata dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri seperti Cilegon, dan Gresik, yang melaporkan meningkatnya penyakit ISPA, iritasi kulit, hingga menurunnya kualitas hidup akibat pencemaran.
Di Jakarta, polusi udara diperkirakan berkontribusi pada lebih dari 10.000 kematian dini setiap tahun, serta ribuan kasus rawat inap dan penyakit anak. Studi internasional mencatat kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan mencapai Rp 44 triliun per tahun. Di Banten, polusi dari PLTU Suralaya yang menopang kawasan industri juga menyebabkan ribuan kematian dini, dengan kerugian mencapai Rp 14–16 triliun per tahun. Universitas Indonesia sejak lama sudah menegaskan bahwa paparan polutan seperti NO₂ membuat anak-anak kehilangan hari belajar, sementara pekerja kehilangan hari produktif. Semua ini menunjukkan betapa mahalnya biaya yang ditanggung publik.
Jika angka kerugian ini kita bandingkan dengan potensi penerimaan pajak yang hilang akibat tax holiday, terlihat jelas betapa besar subsidi terselubung yang dinikmati industri. Bayangkan Rp 44 triliun yang hilang akibat dampak kesehatan dari polusi bisa digunakan untuk membangun ratusan rumah sakit daerah baru, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, memperbaiki ribuan sekolah yang rusak atau mendanai program besar-besaran pemulihan lingkungan. Artinya, negara sebenarnya memilih mengorbankan kesehatan dan lingkungan rakyat demi memberi keringanan pajak pada industri yang justru merusak.
Kritik terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai lembaga riset. The Prakarsa (2024) menyoroti bahwa tax holiday untuk industri plastik dan petrokimia bukan hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga memperburuk krisis lingkungan. Nexus3 Foundation bersama IPEN menegaskan bahwa insentif fiskal semacam ini mendorong ekspansi produksi plastik baru, padahal dunia sedang berjuang melalui Perjanjian Global tentang Polusi Plastik untuk mengurangi produksi plastik, terutama jenis plastik sekali pakai yang paling bermasalah. Dengan kata lain, Indonesia justru berjalan berlawanan dengan tren global.

Pada akhirnya, tax holiday di sektor petrokimia lebih tepat disebut sebagai subsidi untuk perusakan daripada investasi pembangunan. Negara kehilangan potensi pajak triliunan rupiah, sementara rakyat harus menanggung biaya kesehatan dan kerusakan lingkungan. Jika kebijakan ini dibatasi atau bahkan dihapus, Indonesia bukan hanya mendapat tambahan penerimaan negara, tetapi juga mengurangi beban ekologis dari produksi plastik di hulu, yang pada gilirannya akan mengurangi pencemaran plastik di hilir.
Menghentikan tax holiday bagi industri petrokimia berarti memilih untuk berinvestasi pada masa depan masyarakat dan bumi, bukan pada polusi dan kerusakan. (Kia)