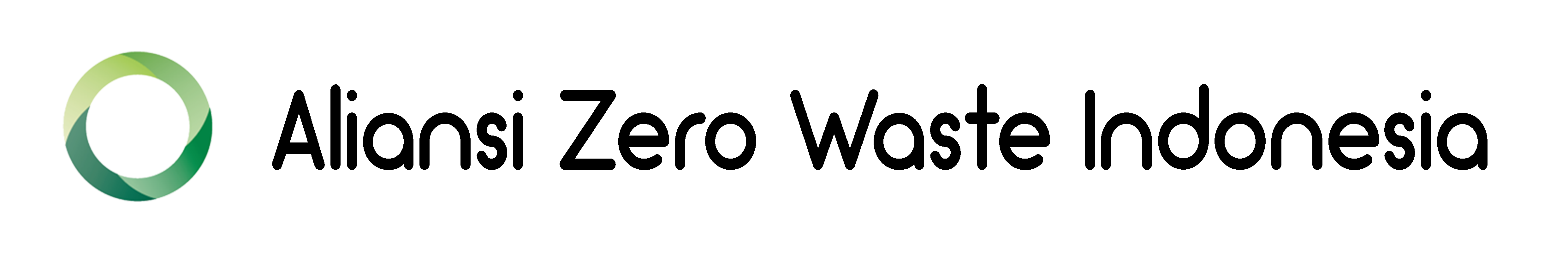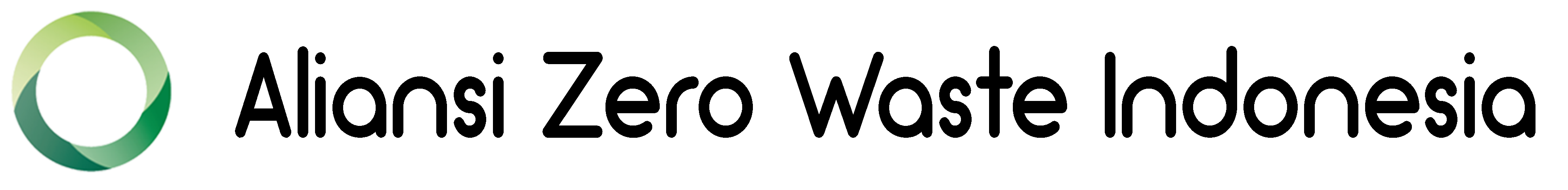Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia menjadi daerah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bagaimana tidak? kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global kian mengancam daerah pesisir Indonesia. Bukan hanya mengancam daerah pesisir dan membuatnya tenggelam, perubahan iklim juga membawa dampak buruk pada kestabilan ekonomi, sosial, dan bahkan bisa menimbulkan bencana berkepanjangan yang kian menurunkan kesempatan masyarakat Indonesia menikmati penghidupan yang layak dan berkelanjutan.
Kini krisis iklim sudah terjadi dan sudah terasa. Tahun lalu cuaca ekstrem dan pandemi COVID-19 menjadi hantaman ganda bagi jutaan warga berbagai benua. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terhangat yang pernah tercatat meski La Nina yang dingin sedang berlangsung, dan suhu yang ekstrem ini menyebabkan 5 juta orang meninggal setiap tahun. Lebih dari 30 juta orang terpaksa mengungsi akibat peristiwa bencana yang dipicu cuaca buruk. Di Indonesia, sekitar 6,3 juta penduduk mengungsi karena terdampak bencana hidrometeorologi seperti hujan, banjir, atau tanah longsor.
Suhu rata-rata global tahun lalu 1,2 derajat Celsius lebih tinggi ketimbang era pra-industri (1850–1900). Padahal, sesuai target bersama, dunia ingin menahan agar kenaikan temperatur jangan sampai melebihi 1,5 derajat Celcius, sembari membidik Net Zero Emission (NZE) global pada 2050 demi menjaga agar bumi tetap nyaman dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.
Indonesia memiliki peran penting untuk ikut mengerem peningkatan suhu bumi. Sebagai negara dengan tutupan hutan tropis luas, Indonesia berpotensi menjadi negara climate superpower yang bakal menentukan arah untuk menghadapi krisis iklim.
Namun, ini memerlukan ambisi dan konsistensi tinggi dari Indonesia. Sebab, saat ini industri ekstraktif dan tinggi emisi karbon masih mendominasi ekonomi nasional dan preferensi kebijakan di Indonesia. Tak hanya itu, beberapa pelonggaran aturan terhadap industri kotor kerap terjadi. Misalnya, penambangan dan pengolahan batubara memperoleh perpanjangan izin dan pengurangan royalti, moratorium kelapa sawit tidak dilanjutkan, subsidi masih diberikan untuk energi kotor. Dana stimulus hijau pemulihan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4% dari total USD 6,3 triliun, sementara 96% digunakan bagi kegiatan business as usual (BAU) yang membuka peluang kerusakan lingkungan.
Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Chenny Wongkar mengatakan Indonesia perlu berinovasi dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai target dimaksud. Rencana pembangunan harus hijau, adil, dan seimbang. Tidak hanya memburu pertumbuhan, tapi juga bertumpu pada kesejahteraan bersama serta kesadaran menjaga lingkungan.
“Pembangunan semacam ini harus mengedepankan jaminan bahwa kondisi lingkungan hidup tetap terjaga, menunjang kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi krisis iklim,” kata Chenny dalam konferensi pers ‘Pesan Untuk Jokowi Menjelang COP26’ beberapa waktu lalu.

Untuk menunjukkan capaian atas pembangunan semacam itu, Chenny menjelaskan sejumlah indikator, diantaranya yakni masyarakat memiliki udara bersih dan bebas dari pencemaran, pembangunan tidak mengeksploitasi sumber daya esensial dan merusak lingkungan, serta kebutuhan dasar seperti energi, pangan, kesehatan, dan sanitasi dapat terjamin pemenuhannya.
Tak hanya itu, Chenny juga memaparkan bahwa Indonesia perlu menghentikan model ekonomi ekstraktif yang berfokus pada keuntungan jangka pendek dan beralih pada ekonomi hijau dengan keuntungan jangka panjang. Langkah yang bisa diambil adalah segera beralih dari sumber energi berbasis fosil—seperti batubara dan turunannya—menuju energi terbarukan. Sebab, sektor energi harus menjadi fokus peningkatan ambisi kebijakan iklim Indonesia.
“Kemudian, pelibatan inklusif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dan perwujudan konsepsi keadilan iklim dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas yang berketahanan iklim pada 2045,” jelasnya.
Sementara itu, Deon Arinaldo dari Institute for Essential Services Reform (IESR) juga mengamini hal yang sama. Menurutnya, 91% transportasi domestik saat ini masih didominasi energi fosil. Dampak praktik tersebut buruk bagi lingkungan, sosial, dan keuangan negara. Seperti kerusakan hutan, korban lubang tambang, dan besarnya impor BBM. Jika transisi energi hanya dilakukan pada sumber energi tak terbarukan seperti batu bara cair atau gas, peralihan menuju energi terbarukan sesungguhnya malah akan terhambat.
“Indonesia perlu transisi secara menyeluruh dari sumber energi berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan,” ungkap Deon dalam kesempatan yang sama.
Satu hal bertaut dengan hal lain. Menurut Salma Zakiyah dari Yayasan Madani Berkelanjutan, untuk mencapai target NZE, hutan diperlukan sebagai penyerap emisi. Sedangkan, industri energi berbasis fosil terbukti merusaknya. Dalam perang melawan krisis iklim, kunci kemenangan bisa diraih dengan melindungi dan memulihkan ekosistem alam.
“Ekosistem gambut, hutan, mangrove, dan laut adalah penyerap karbon yang luar biasa dan vital dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim,” ujarnya.
Selain masalah energi fosil, hal krusial yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah pengelolaan sampah yang hingga saat ini tidak berjalan dengan baik. Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia, Yobel Novian Putra, target NZE alias nol emisi pun perlu didorong dari sektor sampah. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh sejak dari produksi hingga konsumsi.
Selama ini, kata Yobel, setiap warga kota menghasilkan 50-60% sampah organik khususnya sampah makanan. Namun, sarana prasarana penanganan sampah yang terbatas menyebabkan sebagian besar dari sampah ini dibuang di lahan terbuka. Alhasil, sampah yang tak terolah berpotensi melepaskan gas metana yang puluhan kali lipat lebih berbahaya dari gas karbon dioksida bagi iklim kita.
Dalam laporan terakhirnya, IPCC menyerukan agar penanganan gas metana menjadi prioritas pembahasan pada COP26. Di Indonesia, gas metana sebagian besar dilepaskan dari sektor limbah (waste sector), terutama dari TPA sampah yang masih beroperasi dalam bentuk open dumping. Tapi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, emisi sektor limbah diproyeksikan hanya berkurang sebesar 40 MT CO2-e atau 1.4% dari praktik saat ini (BAU).
“Setidaknya ada 514 TPA sampah kota/kabupaten yang masih open dumping yang diproyeksikan melepas gas metana sebesar 296 Mega Ton (296 juta ton) CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Angka ini akan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya jika kita tidak fokus pada upaya pengurangan sampah,” ujar Yobel.
Yobel melanjutkan, seyogyanya pengelolaan sampah harus difokuskan sejak dari hulu alias produsen dengan menegakkan Extended Producer Responsibility (EPR), yang mewajibkan produsen mengubah desain kemasan dari sekali pakai menjadi isi ulang. Semua kemasan yang diproduksi harus bisa didaur ulang, atau tidak menggunakan bahan berbahaya.
Di sisi hilir (konsumen), pemerintah perlu menjatuhkan sanksi tegas bagi mereka yang tidak memilah sampah di sumber. Konsumen juga perlu difasilitasi untuk memilah dan mendaur ulang sampahnya. “Jika hanya fokus pada hilir, tak akan menyelesaikan masalah,” kata Yobel.
Bukan hanya upaya pengurangan dari sumber, Yobel juga menilai teknologi termal seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Refused Derived Fuel (RDF) — atau pembakaran sampah — perlu dihapuskan sebagai ‘teknologi ramah lingkungan’ dari dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) maupun kebijakan sektor sampah Sebab, membakar sampah di insinerator, gasifikasi dan pirolisis untuk mengurangi volume sampah di beberapa kota ini tidak realistis, memakan biaya tinggi dan berpotensi gagal.
Selain itu, teknologi tersebut masih menghasilkan emisi gas rumah kaca serta abu beracun dan senyawa kimia berbahaya lainnya sebagai produk sampingan dari proses pembakaran tidak sempurna. Kebijakan ini juga akan melemahkan upaya pemerintah, masyarakat dan badan usaha untuk mendorong upaya penggunaan kembali dan daur ulang sampah sebanyak 30% pada 2030, yang juga sudah tertuang dalam NDC.
Jika langkah-langkah di atas kurang mengena, maka pemerintah bisa mendorong skema pembiayaan yang merangsang ekonomi hijau. Brurce Mecca dari Climate Policy Initiative (CPI) mengatakan banyak anggaran yang beralih ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Alhasil, anggaran iklim tidak menjadi prioritas.
“Tantangannya, jangan sampai pergeseran ini terjadi untuk jangka panjang. Anggaran jangka panjang tetap difokuskan untuk ekonomi hijau,” kata dia.
Pemerintah perlu membuat kebijakan yang menarik bagi investasi hijau. Misalnya dengan memberi insentif bagi investasi hijau dan disinsentif bagi investasi sektor kotor. Insentif ini bisa dilakukan bagi pemerintah daerah. Seperti dengan mendorong Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus untuk penganggaran energi hijau. Dengan kebijakan ini, investasi hijau dari swasta dan luar negeri diharapkan dapat terbetot.
Dari semua saran di atas, dapat dirangkum bahwa Indonesia memang harus segera berbenah untuk bisa mengerem krisis iklim yang sudah ada di depan mata. Menjelang perhelatan akbar berskala internasional tentang perubahan iklim yang disebut Conference of the Parties (COP) yang akan digelar pada 1-12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, diharapkan para pemimpin dunia termasuk Indonesia bisa membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim tingkat global.
Untuk itu, berikut pesan dari Komunitas Peduli Krisis Iklim kepada pemerintahan Joko Widodo menjelang COP 26:
- Memastikan arah pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, berkeadilan, berorientasi pada pertumbuhan kesejahteraan, dan responsif terhadap Krisis Iklim, melalui pemenuhan ambisi Net Zero Emission lebih cepat dari 2060 melalui peta jalan yang jelas dan terukur;
- Memastikan peralihan segera dari sumber energi berbasis fosil seperti batu bara dan turunannya menuju energi terbarukan, dengan kebijakan transisi energi yang inklusif, terdesentralisasi, terukur, dan berkeadilan;
- Memastikan penguatan upaya perlindungan ekosistem alam, termasuk menghentikan alih guna lahan yang tidak selaras dengan aspirasi Indonesia mencapai Net Zero Emission lebih cepat dari 2060.
- Memastikan pengelolaan sampah yang menyeluruh, mulai dari pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Memastikan Indonesia menjadi negara tujuan investasi hijau yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memperbesar insentif aliran pendanaan hijau dan disinsentif pendanaan kotor.
Sebagai informasi, COP 26 singkatan dari Conference of the Parties atau Pertemuan Para Pihak, tahun 2021 ini adalah pertemuan yang ke 26. COP merupakan forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara, untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana negara-negara di dunia berencana untuk menanggulanginya.
COP 26 adalah bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim – yaitu perjanjian internasional yang ditandatangani setiap negara dan teritori di dunia yang bertujuan membatasi dampak aktivitas manusia atas iklim. (Kia)